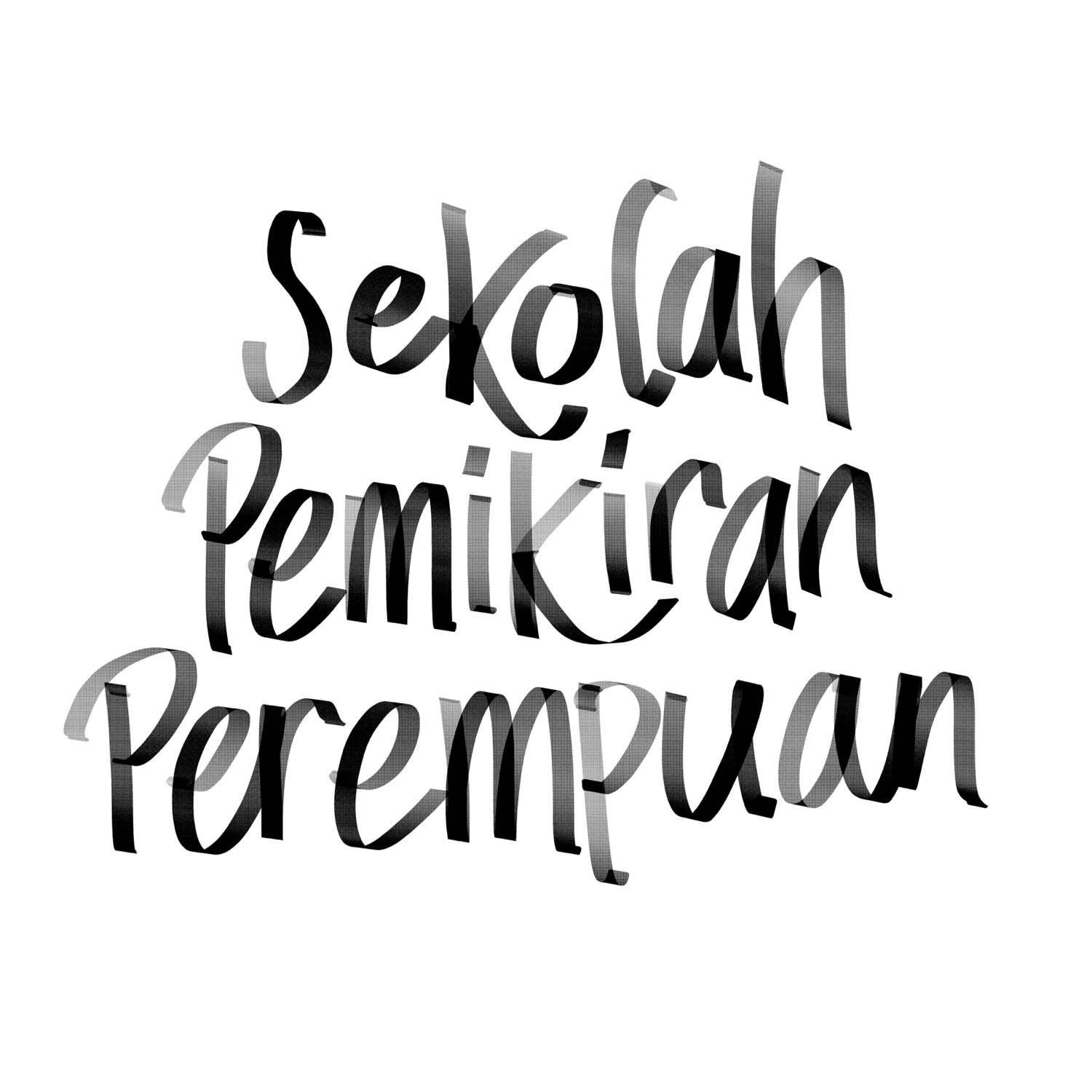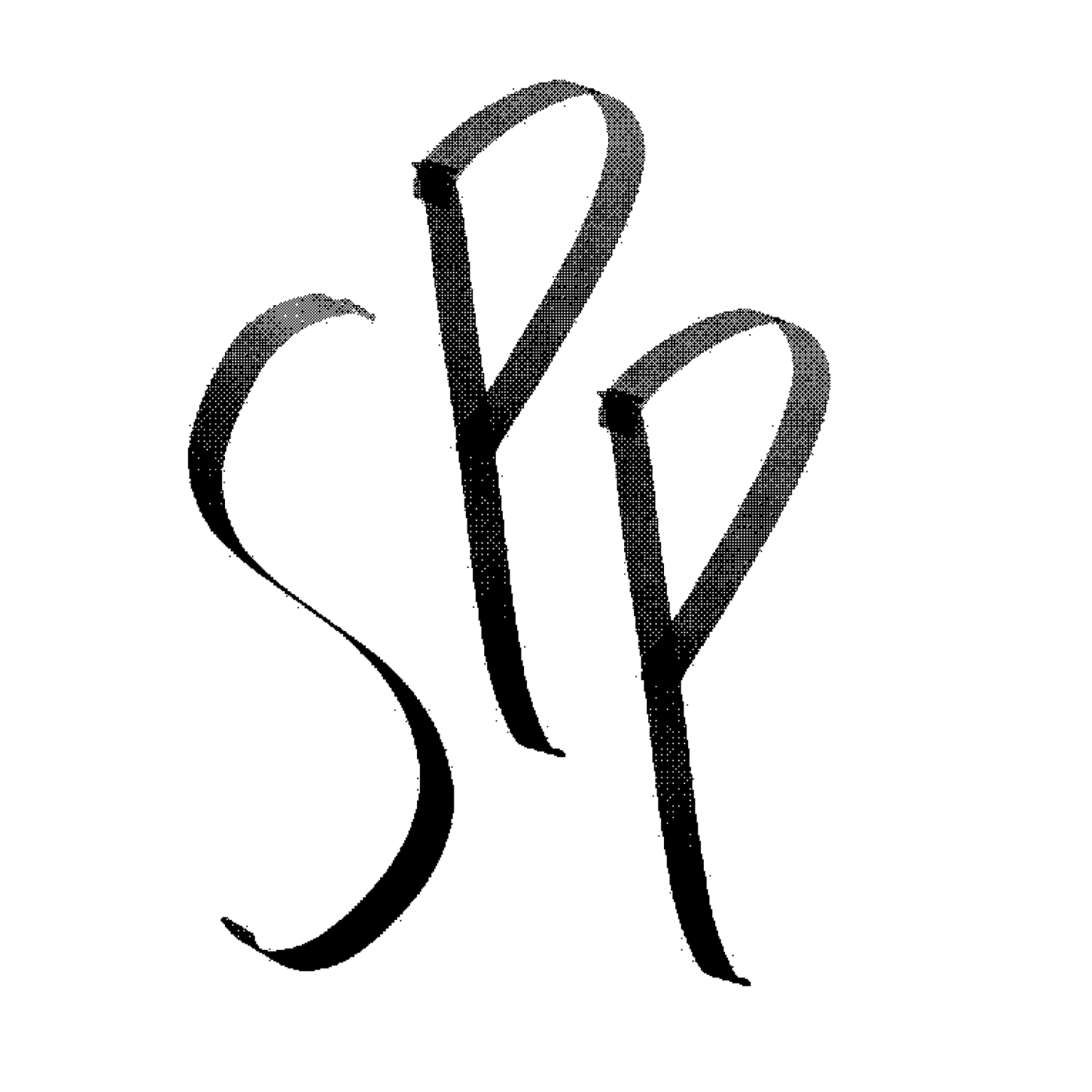Laman ini masih akan terus diperbaharui. Pengkinian terakhir: 22 September 2025 16:00 WIB.
Panelis | Panelists
-

Martha Hebi
(Penulis dan Relawan SOPAN Sumba)
Martha Hebi lahir di Waingapu, Sumba Timur. Sejak 2003 ia bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat Pulau Sumba. Proses kerjanya melahirkan refleksi tentang diskriminasi perempuan serta pengabaian terhadap nilai kemanusiaan dalam sejarah dan tradisi lokal. Martha melakukan riset, perjumpaan dan sharing dengan perempuan penyintas, perempuan yang suaranya jarang terdengar dan didengarkan. Juga isu kelompok rentan, kekerasan berbasis tradisi. Dia juga mendokumentasikan suara penyintas, perempuan-perempuan ini, kelompok rentan lainnya lewat tulisan-tulisannya baik fiksi dan non fiksi.
-

Yustina Dama Dia
(Direktur SOPAN Sumba)
Yustina Dama Dia atau Yustin adalah perempuan kelahiran Sumba Tengah, 27 Juli 1988. Saat ini Yustin adalah Direktur Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba, sebuah lembaga lokal yang fokus pada isu perempuan, anak, orang dengan disabilitas dan kelompok marginal lainnya seperti Marapu (agama lokal Sumba). Dia menjabat sebagai Direktur SOPAN Sumba sejak tahun 2021 hingga saat ini. Empat tahun terkahir ini Yustin bersama Relawan SOPAN lainnya fokus untuk melakukan advokasi bagi korban dan penyintas kawin tangkap, kawin anak, kekerasan terhadap perempuan. Dia membangun jaringan lokal dan nasional untuk gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan ini.
-

Brigitta Isabella
(Peneliti)
Brigitta Isabella menjumpai dan memediasi orang, objek, dan diskursus melalui berbagai wadah produksi pengetahuan dalam persilangan antara sejarah seni, teori kritis, dan aktivisme kebudayaan. Ia adalah anggota Forum dan Kolektif Belajar KUNCI sejak 2011 dan kini mengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain, ISI Yogyakarta. Brigitta telah menyunting beberapa buku antara lain Unjuk Rasa: Seni, Performativitas, Aktivisme (Kelola, 2018), Dari Pembantu Seni Lukis Kita: Bunga Rampai Tulisan Oei Sian Yok 1956-1961 (Dewan Kesenian Jakarta& Gang Kabel, 2019), Mengasah Asuh: Ibu-Pekerja Migran, Kerja Pengasuhan dan Kasih Revolusioner (Beranda Perempuan Migran, 2023), dan Beribu Surat: Antologi Surat Feminis dari Indonesia (bersama Shinta Febriany, Peretas, 2024). Saat ini ia tengah meneliti hubungan antara seni konseptual, kerajinan tangan, dan ekonomi politik kerja informal di era Orde Baru.
-

Ruth Indiah Rahayu
(Aktivis Gerakan Literasi IndoProgress)
Doktor di bidang filsafat yang bekerja sebagai peneliti, pengajar dan penulis.
-

Taomo Zhou
(Associate Professor and Dean's Chair, Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore)
Taomo Zhou adalah Associate Professor di Departemen Chinese Studies dan Dekan di Fakultas Seni dan Ilmu Sosial, National University of Singapore. Buku pertamanya, Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia and the Cold War (Cornell University Press, 2019), memenangkan penghargaan “Best Books of 2020” award and an Honorable Mention for the 2021 Harry J. Benda Prize dari Association for Asian Studies.
-

Isabella Hammad
(Penulis)
Isabella Hammad adalah seorang penulis yang karya terbarunya Recognizing the Stranger dan karya lainnya, novel Enter Ghost, telah menerima penghargaan dari Aspen Prize, Clark Prize, and Encore Award. Ia telah mengajar sastra dan penulisan kreatif di New York University, Brown University, dan Al Quds Bard College. Karyanya telah didukung oleh Lannan Foundation, Columbia University's Institute for Ideas and Imagination, dan Dorothy and Lewis B. Cullman Center for Scholars and Writers di New York Public Library.
-
Bunga Siagian
(Seniman dan Peneliti)
Bunga Siagian adalah seniman, kurator, dan produser budaya, yang tinggal dan bekerja di Jatiwangi dan Depok. Menyelesaikan studi masternya pada ilmu Cultural Studies. Memiliki ketertarikan dengan sejarah jaringan Asia-Afrika, internasionalisme Dunia Ketiga, dan komitmen politik-sinematik kelompok kiri pada era dekolonisasi. Praktik kekaryaannya sering mengambil bentuk institusi publik, seperti Mother Bank dan BKP (Badan Kajian Pertanahan), proyek riset artistik yang fokus pada isu perempuan dan pertanahan dengan menempatkan praktiknya pada titik temu antara seni dan pengamalan kerja kolektif.
-

Ilda Karwayu
(Penulis, Pengajar, Creative Director)
ILDA KARWAYU tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB); menulis prosa dan puisi. Telah menerbitkan sejumlah buku puisi, antara lain: EULOGI (PBP, 2018), dan Binatang Kesepian dalam Tubuhmu (GPU, 2020)—yang pada 2022 masuk nomine Penghargaan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pernah hadir sebagai salah satu emerging writers dalam Makassar International Writers Festival (MIWF) 2019. Pun, pada 2021 dan 2022 hadir sebagai salah satu panelis di MIWF serta Festival Sastra Banggai. Setahun kemudian, turut mengelola Satelit Program Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2023 di Kota Jambi dan Mataram—setelah sebelumnya mengisi panel di Ubud. Sejak 2012 belajar menulis, serta memanajeri rangkaian program sepanjang 2017 s.d. 2023, di Komunitas Akarpohon Mataram. Tahun 2022, berkesempatan belajar di Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP), dan selanjutnya turut bergiat pada sejumlah program. Gres, menjadi Co-director untuk MIWF 2024 dan 2025.
[Foto oleh Aziziah Dyah Aprilia]
-
Maria Apriani Kartika Solapung
(Praktisi Seni, bergiat di Komunitas KAHE, Maumere)
Kartika Solapung adalah seorang praktisi seni yang berbasis di Maumere. Sejak 2016 bergiat dalam kerja-kerja kesenian dan kebudayaan bersama Komunitas KAHE. Terlibat dalam berbagai penelitian, penciptaan pertunjukan teater dan musik, serta memproduksi pameran dan festival. Alumni Sekolah Pemikiran perempuan 2022. Beberapa tulisan dimuat di website Laune.id. Menjadi fasilitator bagi seniman, musisi, penari, untuk residensi di dalam maupun luar negeri. 2025 menjadi produser Festival Maumerelogia 5 di Maumere. Saat ini sedang mengikuti program Magang Produser Kelola di Jakarta.
-

Ligia Judith Giay
(Staff Pengajar STT Walter Post Jayapura)
Ligia Giay menempuh pendidikan di bidang Sejarah dan kini bekerja sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura. Minatnya terutama adalah sejarah daerah Timur Indonesia pada masa kolonial Belanda. Ia sering membaca, sedikit menulis.
-

Zely Ariane
(Pekerja komunitas aktif di Yapkema Papua)
Peminat isu-isu pembebasan yang disekolahkan oleh gerakan mahasiswa dan politik kiri Indonesia dan didewasakan oleh pemikiran gender, interseksionalitas, pembebasan nasional dan pergerakan masyarakat asli.
-

Astrid Reza
(Sejarawan)
Astrid Reza menempuh pendidikan studi sejarah di Universitas Gadjah Mada, dengan fokus studi sejarah perempuan Indonesia. Tengah menyelesaikan studi S2 di Kajian Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Menulis lepas di berbagai media, dari sastra sampai riset sejarah. Telah menerjemahkan berbagai buku bertema sosial, sejarah, feminisme dan sastra. Saat ini terlibat sebagai co-founder dan anggota aktif RUAS (Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan) Indonesia di Yogyakarta.
-

Ishvara Devati
(Seniman Tari)
Ishvara Devati adalah seniman tari yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Ia berfokus pada eksplorasi interdisipliner dalam seni pertunjukan. Praktik artistiknya cenderung mengeksplorasi gagasan tentang identitas trans gender perempuan, transhumanisme, tubuh post-digital serta interaksi antara teknologi dan transformasi tubuh.
Ishvara telah berpartisipasi dalam berbagai lokakarya seperti CP[3] oleh Dance Nucleus, Feminist Activism Tech Camp oleh PurpleCode, dan Sekolah Pemikiran Perempuan. Karyanya telah dipentaskan di Indonesia maupun secara internasional, termasuk film tari less than an ounce di Indonesia Bertutur 2024, dan karya pertunjukan instruksional Deliberated Weirdness di Festival Avant-Garten di Hamburg, Theater der Welt di Jerman, dan Theater Spektakel di Swiss. Karyanya yang berjudul The Synthetics of Hybrid Beings juga dipresentasikan sebagai karya tumbuh di Indonesian Dance Festival 2024.
Ishvara aktif terlibat dalam berbagai residensi seperti Invisible Dance – The Body in Friction di Ahmedabad, India; Farm-Lab Exhibition di Tokyo, Jepang; ARTEFACT#11 – Dance Nucleus, Singapura; dan Experimental Choreographic Program Residency – Performance Space, Australia. Ia juga berkolaborasi secara internasional dengan berbagai seniman, seperti dalam proyek Bodies of Care bersama seniman dari Jerman
-

Marta Ying
Marta Ying lahir di Kampung Tumbit Dayak pada 5 Maret 1965 dari orang tua bernama Lu Ge’ah Nge’au (ibu) dan Isak Tulan (ayah). Beliau adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus pengrajin pakaian tradisional suku Dayak Gaai dan pelantun syair Siu Ma’dem. Beliau aktif melestarikan warisan budaya leluhur, terutama dalam ritual adat yang dilaksanakan pada Festival Budaya Bekudung (pesta panen). Dalam setiap perayaan tersebut, Ibu Marta Ying memimpin prosesi naik ke “rumah tinggi”– tradisi turun-temurun yang diwarisi dari orang tuanya.
-

Mama Thea Gifelem
Mama Thea Gifelem adalah seorang perempuan Moi yang lahir di Sorong, papua Barat Daya. Ia adalah seorang ibu, pengrajin noken, dan praktisi tradisi lisan Kain Kla. Saat ini ia tinggal di Kilo 9, Kota Sorong. Mama Thea hidup sangat dekat dengan hutan, hingga hari ini ia bersama dengan Mama Antonia masih sering naik ke kampung. Mama Thea meraih Juara 2 pada lomba Kain Kla Festival Tumpe Klawalu 2025, sebuah festival yang mengangkat budaya Suku Moi di Kota Sorong.
-

Mama Antonia Ulimpa
Mama Antonia Ulimpa dikenal sebagai seorang perempuan yang penuh senyum dan semangat. Ia tinggal di Kilo 9, Kota Sorong, dan sehari-hari berkebun di halaman. Selain menjadi empu Kain Kla, ia juga aktif memasak pangan tradisional Moi seperti ikan bambu, olahan ulat sagu, dan papeda. Ia juga terlibat dalam grup tari Alen di Kilo 9, sebuah tarian grup yang diiringi oleh lantunan syair dan tabuhan gong. Mama Antonia turut ikut serta dalam perlombaan Kain Kla di Festival Tumpe Klawalu 2025, di mana ia meraih juara 2.
-

Gema Swaratyagita
Gema Swaratyagita adalah seorang komponis dan pendidik musik, yang banyak bergerak di ranah seni interdisipliner dan kolaborasi lintas disiplin. Sejumlah karyanya telah dipertunjukkan di berbagai festival nasional dan internasional seperti International Gamelan Festival, Pekan Komponis Indonesia, Gulali Festival, hingga Holland Festival. Kecintaannya pada dunia pendidikan, kemudian membuatnya mendirikan Bumi Bunyi : Creative Music Education dan juga merupakan co-founder Perempuan Komponis Forum & Lab.
-

Desty Nursyiam
Desty Nursyiam adalah seorang pemusik sekaligus sastrawan Sunda. Dalam musik tradisional, dia memainkan alat musik Kendang dan Tarawangsa, dua alat musik yang jarang sekali dimainkan oleh perempuan. Karya sastranya berupa sajak Sunda banyak menyuarakan tentang kesetaraan, isu lingkungan dan isu sosial. Bersama Yayasan Puspa Karima Indonesia dia bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dalam seni budaya, khususnya musik tradisional Sunda.
-
Ayu Permata Sari
Ayu Permata Sari adalah koreografer dan penari asal Lampung Utara yang memimpin Ayu Permata Dance Project (APDP). Karyanya menjadikan tubuh sebagai ruang negosiasi dan kritik terhadap relasi kuasa dalam masyarakat Lampung Pepadun, khususnya posisi perempuan dalam sistem patriarki dan adat. Melalui tari, Ayu membongkar batas antara ekspresi personal, warisan budaya, dan resistensi sosial.
-
Salsabila Andriana
Salsabila Andriana adalah seorang praktisi budaya dan desainer multidisplin yang mendalami seni dan pangan lokal di wilayah Sorong, Papua Barat Daya. Ia mendirikan Lumbung Sagu Collective, sebuah kolektif yang bertujuan mendokumentasikan dan mempopulerkan kembali pengetahuan lokal ekologis yang dimiliki oleh leluhur di Nusantara. Ia juga tertarik dengan tema-tema terkait kedaulatan pangan, dekolonisasi pengetahuan, keadilan iklim, dan hubungan komunitas masyarakat adat.
-

Rosyidah
Rosyidah adalah pelukis dan ilustrator asal Berau, Kalimantan Timur. Ia merupakan salah satu pendiri Ruang Perupa, sebuah komunitas yang mewadahi ruang belajar seni visual lintas disiplin dan lintas generasi. Saat ini, ia tengah mendalami praktik pengarsipan pengetahuan lokal dan seni budaya di Berau melalui pendekatan seni kolaboratif. Minatnya mencakup pengarsipan narasi lokal, seni rupa eksperimental, serta pendekatan feminisme dekolonial.
-

Mirat Kolektif
Mirat Kolektif diinisiasi pada 2018 di Surakarta dan berdiri pada 2020. Berawal dari kebutuhan akan ruang aman untuk berbagi ide dan proses kreatif, Mirat Kolektif mengembangkan laboratorium penciptaan seni berbasis riset sebagai ruang produksi pengetahuan yang berangkat dari kenyataan sosial atas peminggiran, pengerdilan, atau penghapusan pengetahuan masyarakat minoritas dengan menggunakan pemikiran, kerja, dan etika feminis untuk dipresentasikan kepada publik. Mirat Kolektif tidak hanya berfokus pada seni pertunjukan, tapi juga membuka diri pada kemungkinan bentuk-bentuk kreatif lainnya.
Moderator
-

Tyassanti Kusumo
(Peneliti)
Tyassanti Tinggal di Surakarta, menaruh minat pada riset mengenai pengelolaan warisan budaya, koleksi perpustakaan, dan koleksi asal usul. Sehari-hari beraktivitas di instansi kebudayaan sembari menggarap proyek kuratorial, editorial, dan riset partikelir.
-

Lisabona Rahman
(Arsiparis & Programmer Film)
Lisabona Rahman mengelola proyek presentasi film, arsip dan karya perempuan sejak 2001. Ia belajar pelestarian film dan kuratorial di Belanda, lalu bekerja sebagai teknisi restorasi film di Italia sampai 2016. Kemudian ia bekerja lepas membuat proyek restorasi, perawatan film, pemutaran dan forum pertukaran pengetahuan. Pada 2018, ia memulai Sekolah Pemikiran Perempuan bersama Andy Yentriyani, Cecil Mariani, Heidi Arbuckle Gultom, Intan Paramaditha, Naomi Srikandi dan Nya’ Ina Raseuki untuk menambah ruang belajar mengenai feminisme dan sejarahnya di kepulauan Indonesia. Mulai 2021, Lisabona bergabung ke kolektif riset pelestarian film, restorasi dan karya perempuan Kelas Liarsip bersama Efi Sri Handayani, Imelda Taurina Mandala, Julita Pratiwi, Umi Lestari dan Siti Anisah.
-

Intan Paramaditha
(Penulis dan Akademisi)
Intan Paramaditha adalah penulis novel Gentayangan (2017), buku yang meraih English PEN Translates Award, nominasi Stella Prize, dan karya sastra prosa terbaik Majalah Tempo. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Polandia, Turki, Thailand, Italia, dan Jepang. Kumpulan cerpen Sihir Perempuan adalah buku pertamanya, terbit pada tahun 2005 dan masuk ke dalam lima besar Kusala Sastra Khatulistiwa. Sebagian cerpen Sihir Perempuan terbit dalam kumpulan cerpen Apple and Knife, bagian dari seri Vintage Classics “Weird Girls.” Intan merupakan penggagas dan pengelola Sekolah Pemikiran Perempuan, kolektif feminis dekolonial lintas Nusantara. Ia mendapat gelar doktor dari New York University dan bekerja sebagai dosen kajian media di Macquarie University, Sydney. Novel terbarunya adalah Malam Seribu Jahanam (2023).
-

Martha Hebi
(Penulis dan Relawan SOPAN Sumba)
Martha Hebi lahir di Waingapu, Sumba Timur. Sejak 2003 ia bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat Pulau Sumba. Proses kerjanya melahirkan refleksi tentang diskriminasi perempuan serta pengabaian terhadap nilai kemanusiaan dalam sejarah dan tradisi lokal. Martha melakukan riset, perjumpaan dan sharing dengan perempuan penyintas, perempuan yang suaranya jarang terdengar dan didengarkan. Juga isu kelompok rentan, kekerasan berbasis tradisi. Dia juga mendokumentasikan suara penyintas, perempuan-perempuan ini, kelompok rentan lainnya lewat tulisan-tulisannya baik fiksi dan non fiksi.
-

Asri Pratiwi Wulandari
Ulan (Asri Pratiwi Wulandari) adalah penerjemah sastra (Jepang-Indonesia) asal Tanjung Priok. Ia menulis kumcer Yang Menguar di Gang Mawar (Buku Mojok, 2021). Alumni SPP 2023 dan Kajian Gender UI. Selain di SPP, juga pernah terlibat di Jurnal Perempuan. Penerima Toeti Heraty Scholarship 2023. Sedang mengerjakan inisiatif yang berangkat dari arsip perempuan bersama POST Press dan kawan-kawan, di sela-sela menerjemahkan dan belajar jahit.
-

Himas Nur
Himas Nur merupakan alumni Kelas Sekolah Pemikiran Perempuan 2023. Ia adalah seorang pekerja seni yang mengartikulasikan ekspresi estetik-politik melalui bahasa dan tulisan. Karya-karyanya dekat dengan kelindan keseharian; queer, feminisme, keadilan buruh, kesehatan mental, dan perawatan kolektif. Buku tunggalnya yang telah terbit adalah Bianglala, Komidi Putar, dan Negeri Dongeng (2013), serta Menjelajahi Diri, Memeluk Intimasi: Kajian Panseksualitas di Indonesia (2023). Sehari-hari ia mengajar di Program Studi Film dan Televisi, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
-

Dida Fisandra
Dida Fisandra adalah produser dan manajer seni pertunjukan. Dida merupakan rekan pendiri dan direktur kolektif Perempuan Komponis: Forum & Lab, dan saat ini menjabat sebagai Manajer Program Seni Pertunjukan dan Edukasi-Gagasan di Komunitas Salihara Arts Center. Dengan latar belakang komposisi musik dan antropologi, Dida tertarik mengeksplorasi seni melalui kajian tentang ruang dan media, termasuk isu-isu dekolonisasi dalam lanskap musik kontemporer di Indonesia.
Fasilitator Klinik & Lokakarya
-

Gema Swaratyagita
(Komponis dan Pendidik Musik)
Gema Swaratyagita adalah seorang komponis dan pendidik musik, yang banyak bergerak di ranah seni interdisipliner dan kolaborasi lintas disiplin. Sejumlah karyanya telah dipertunjukkan di berbagai festival nasional dan internasional seperti International Gamelan Festival, Pekan Komponis Indonesia, Gulali Festival, hingga Holland Festival. Kecintaannya pada dunia pendidikan, kemudian membuatnya mendirikan Bumi Bunyi : Creative Music Education dan juga merupakan co-founder Perempuan Komponis Forum & Lab.
-

Nyak Ina Raseuki
(Pesuara, Improviser, Komposer dan Etnomusikolog)
Nyak Ina Raseuki atau biasa dipanggil Ubiet, seorang pesuara, improviser, komposer dan etnomusikolog. Penjelajahan Ubiet di bidang suara dan nyanyian dimulai dengan penemuannya akan keragaman teknik, warna suara, dan ornamen yang dipraktikkan dalam berbagai tradisi nyanyian di Nusantara. Kini, ia fokus pada eksplorasi suara dan nyanyian tidak hanya sebagai bentuk ekspresi musik, tetapi juga dalam konteks keragaman pengetahuan dan ekspresi budaya serta sejarah dalam komunitas yang beragam. Selain komitmennya terhadap riset musik, Ubiet terus berkolaborasi dengan komposer, musisi populer, dan seniman tradisional dalam berbagai pertunjukan dan rekaman.
Beberapa rekaman yang telah dirilisnya antara lain bersama New Jakarta Ensemble, Commonality (Siam Record, New York, 1999), Archipelagongs (Warner Music Indonesia, 1999), Music for SoloPerformer:Ubiet Sings Tony Prabowo (Musikita, Jakarta, 2006), Ubiet & Kroncong Tenggara (demajors, Jakarta, 2007/2013), dan yang terkini, Olaijolo, musik berbasis nyanyian perempuan Indonesia Timur (BIR, Jakarta, 2024).
-

Kelas Liarsip
Kelas Liarsip merupakan kolektif periset yang meletakkan perhatian pada studi arsip, restorasi, dan historiografi karya film ciptaan perempuan dalam Sinema Indonesia.
Kolektif ini berawal dari sebuah kelompok belajar virtual yang berdiri pada Maret 2021. Pada 2022, kolektif ini menginisiasi dan menjalankan penelusuran jejak Ratna Asmara - sutradara perempuan pertama yang mengawali karirnya sebagai aktor. Debut pertamanya sebagai sutradara diawali dengan Sedap Malam (1950). Ia aktif membuat film fiksi panjang dari 1950 ke 1954. Sayangnya, hanya satu judul film yang sejauh ini tersimpan, Dr. Samsi (1952) - adaptasi dari naskah teater. Dengan dukungan sejumlah pihak, kolektif ini mengorganisir reparasi dan digitisasi copy positif 35mm dari film tersebut.
-

Lusiana Limono
Lusiana adalah lulusan Pascasarjana IKJ Penciptaan Artistik yang memiliki ketertarikan pada isu-isu lingkungan dan peran perempuan dalam menggunakan kriya sebagai bahasa ekspresi serta reproduksi pengetahuan di ruang domestik. Dia tertarik pada peran kain obyek domestik dalam menciptakan peluang untuk keterhubungan yang lebih dalam antara manusia dan indera terkait ( ruang, kesejahteraaan, identitas, akar). Lusiana telah menerima beberapa penghargaan seperti Good Design Award tahun 2018, "Weaving Tales" Short Story Competition dari Asean Foundation tahun 2021, dan berpartisipasi dalam residensi di wilayah Indonesia (di Lembata, Sumba, dan Riau).
-

Christine Toelle
Christine Toelle adalah seorang praktisi dan peneliti seni budaya yang mengeksplorasi tema materialitas, warisan, dan dekolonisasi. Sebagai alumni Sekolah Pemikiran Perempuan dari latar belakang pendidikan seni rupa dan antropologi sosial, ia menaruh perhatian pada bagaimana pengetahuan dan objek budaya diwariskan, diklaim ulang, dan dinegosiasikan dalam konteks pascakolonial. Praktiknya melibatkan pendekatan interdisipliner terhadap pemulangan objek (repatriasi) dan rematriasi pengetahuan, serta membangun ruang kolaboratif antara arsip, seniman, dan komunitas. Ia aktif menulis dan memfasilitasi diskusi yang mengangkat tafsir tubuh, pengalaman perempuan, dan ingatan kolektif dalam seni.
Christine pernah mempresentasikan gagasannya di berbagai forum seperti British Museum (2025), Royal Anthropological Institute (2024), Cemeti Institute (2024), dan Indian Ocean Craft Triennial (2024). Karya kuratorialnya termasuk pameran di EDSU house (2025), KBRI London dan Anglo-Indonesian Society di Museum of the Home (2024), Sumida Expo Jepang dan SUBO Family (2023–2024), Salihara Art Centre dan ARCOLABS (2022).
-

Cecil Mariani
Cecil Mariani adalah seorang perancang, seniman, peneliti di Prakerti kolektif inteligensia, aktivis budaya dan pengajar di Insitut Kesenian Jakarta. Ia belajar Desain Grafis di Universitas Pelita Harapan dan meraih gelar magister MFA dari School of Visual Art, New York.
Karya Rupa “Telusur Waris”
-

Lusiana Limono
Lusiana adalah lulusan Pascasarjana IKJ Penciptaan Artistik yang memiliki ketertarikan pada isu-isu lingkungan dan peran perempuan dalam menggunakan kriya sebagai bahasa ekspresi serta reproduksi pengetahuan di ruang domestik. Dia tertarik pada peran kain obyek domestik dalam menciptakan peluang untuk keterhubungan yang lebih dalam antara manusia dan indera terkait ( ruang, kesejahteraaan, identitas, akar). Lusiana telah menerima beberapa penghargaan seperti Good Design Award tahun 2018, "Weaving Tales" Short Story Competition dari Asean Foundation tahun 2021, dan berpartisipasi dalam residensi di wilayah Indonesia (di Lembata, Sumba, dan Riau).
Produser & Sutradara Pengantar Tidur
-

Naomi Srikandi
Naomi Srikandi bekerja antara seni pertunjukan dan dramaturgi gerakan feminis, menggunakan estetika sebagai kerangka kerja untuk menyelidiki bagaimana imaji, suara, bahasa dalam keseharian bertimbal-balik dengan politik. Alumni Fisipol Universitas Gadjah Mada dan jebolan Teater Garasi, Yogyakarta ini pernah residensi di DasArts Master School of Theater, Amsterdam dan Hooyong Performing Arts Centre, Wonju. Untuk mempelajari dan menghayati pendekatan feminis interseksional dalam kerja seni-budaya, bersama sejumlah kawan ia turut memulai dan merawat jejaring Peretas, begitu juga Sekolah Pemikiran Perempuan.
-

Luna Kharisma
Luna Kharisma adalah sutradara teater asal Surakarta dan salah satu pendiri Mirat Kolektif. Karya-karyanya banyak menggali pengalaman, perjuangan, dan resistensi perempuan dalam berbagai konteks sosial dan historis. Beberapa karya penyutradaraan yang pernah dipentaskan antara lain Trilogi Di Dalam Rumah (2015-2019), Rapat Rukun Tetangga (2022), Sebagian Pertemuan (2023), Api Kartini Edisi Khusus (2023), Hantu Pada Halaman yang Hilang (2024), dan Sudut Hati Terpercik Api (2025). Selain sebagai sutradara, ia mempunyai minat di bidang musik sebagai seorang vokalis. Luna juga merupakan alumni Sekolah Pemikiran Perempuan 2022.